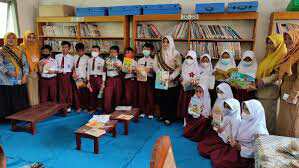Tampilkan postingan dengan label bahasa indonesia 5. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label bahasa indonesia 5. Tampilkan semua postingan
Home » Posts filed under bahasa indonesia 5
(107) a. Penyair Chairil Anwar sangat terkenal.
b. Penyair Chairil Anwar juga dikenal oieh anak muda.
(108) a. Kami terkejut ketika dia datang dengan pakaian adat lengkap.
b. Kami dikejutkan oleh kedatangan dia dengan pakaian
adat lengkap.
Kata pada keiompok (iv), seperti beruntung dan berbahaya^ dapat
diberi pewatas adjektiva seperti paling, lebih, atau agak.
Contoh:
(109) a. Dalam hal ini kami memang beruntung.
aling
b. Dalam hal ini kami memang lebih beruntung.
agak
(110) a. Vetsin berbahaya bagi kesehatan manusia.
paling
b. Vetsin lebih berbahaya bagi kesehatan manusia.
agak
5.7.2 Adjektiva Denominal
Adjektiva denominal tidak terlalu banyak jumlahnya. Ada dua proses
morfologis yang dapat dikemukakan di sini. Yang pertama ialah nomina
yang berprefiks pe{r)- atau peng- seperti pada pemalas dan yang kedua ialah
nomina berkonfiks ke-...-an yang mengalami reduplikasi.
5.7.2.1 Adjektiva Bentuk pe(r)- atau pengKelompok adjektiva ini berasal dari nomina yang mengandung makna
'memiliki sifat ...'.
Contoh:
(111) pelupa
pemalas
pemalu
pemarah
pencemburu
penyabar
pendiam
pengampun
pengasih
penyayang
(112) a. Gadis itu sering menunduk jika diajak berbicara.
b. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
mencintai makhluk-Nya.
c. Meskipun pendiam^ dia mampu berbicara lancar di
depan khalayak.
5.7.2.2 Adjektiva Bentuk ke-...-aii dengan Reduplikasi
Adjektiva yang berpola ke-...-an dengan reduplikasi memerikan sifat mirip
dengan yaitu mirip dengan yang diungkapkan oleh nomina yang menjadi
pangkal bentuk itu. Proses penurunannya adalah melalui pembentukan
nomina abstrak dengan konfiks ke-...-an yang kemudian direduplikasi.
Contoh:
(113) Nomina Nomina Adjektiva Denominal
ibu —► keibuan —> keibu-ibuan
bapak —> kebapakan kebapak-bapakan
kanak kekanakan, kanak-kanak kekanak-kanakan
barat —> kebaratan —> kebarat-baratan
Beianda kebelandaan —> kebelanda-belandaan
(114) a. Meskipun masih muda, gadis itu memiliki sifat
b. Walaupun sudah dewasa, dia sering berperilaku kekanak-kanakan.
c. Sepulang dari Eropa, gayanya berubah kebarat-baratanAdverbia yang lazim disebut kata keterangan adalah kata yang menjelaskan
verba, adjektiva, atau adverbia lain. Hal itu berarti bahwa adverbia digunakan
sebagai pewatas, baik pewatas verba, pewatas adjektiva maupun pewatas
adverbia.
Contoh:
(1) a. Dia ham dataugsctenga\\ jam yang lalu.
b. Keluarganya segera menyttsid.
c. Surat itu belum terkirim,
d. Setlap cahun dia selalu mengirimi saya karcu lebaran.
(2) a. Mobil itu harganya terlalti mahai
b. Lalu lintas di Jakarta lebih padat di Bandung.
c. Walaupun dia bukan penyanyi, suaranya ciiknp merdti.
d. Jika mendengar lagu itu, dia seringsedih karena teringat masa ialunya.
(3) a. Dia higiu sekali berlibur ke Palembang.
b. Meskipun rumahnya jauh, dia sangatjarang datang terlambat.
c. Sejak pertemuan itu, mereka makin sering berkomunikasi.
d. Ketika kami tiba di stasiun, kereta bnru saja berangkat.
Dari contoh di atas dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut.
1) Pada (1) verba datang, menyusul, terkirim, dan mengirimi merupakan inti,
sedangkan adverbia baru, segera, belum, dan selalu adalah pewatasnya.2) Pada (2) adjektiva mahal, padat, merdu, dan sedih merupakan inti,
sedangkan adverbia terlalu, lebih^ cukup, dan sering adalah pewatasnya.
3) Pada (3) terlihat deretan dua adverbia, yang satu sebagai inti dan yang
lain sebagai pewatas. Yang menjadi inti ialah ingin, jarang, sering, dan
baru. Adapun pewatasnya adalah sekali, sangat, makin, dan saja.
4) Berdasarkan konstruksinya, adverbia sebagai pewatas itu ada yang
mendahului inti (pewatas + inti) dan ada pula yang mengikutinya (inti
+ pewatas).
Perlu diingat bahwa dalam Hal deretan dua adverbia, adverbia
pewatas dapat mendahului adverbia inti dan dapat pula mengikuti ad
verbia inti tersebut. Pada contoh berikut terlihat bahwa adverbia pe
watas sangat mendahului adverbia inti jarang (4a) dan adverbia inti yang
sama {jarang dapat pula diikuti adverbia pewatas sekali (4b).
Contoh:
(4) a.
b.
Pak jarang mengunjungi saudaranya di kampung.
Pak Mahmud sangatjarang mengunjungi saudaranya di kampung.
Kami jarang menonton film horor.
Kami jarang sekali menonton film horor.
Adverbia sebagai pewatas verba, adjektiva, atau adverbia lain,
sebagaimana yang telah disebutkan di atas, hanya digunakan sebelum atau sesudah inti. Hal itu berbeda dari adverbia sebagai pewatas kalimat
yang dapat digunakan, baik di awal, di tengah maupun di akhir kalimat.
Contoh: nton
(5) a. Tampaknya dia tidak menyetujui usul itu.
b. Dia tampaknya tidak menyetujui usul itu.
c. Dia tidak menyetujui usul itu tampaknya.
(6) a. Sebenarnya dia ingin cepat-cepat pergi.
b. Dia sebenarnya ingin cepat-cepat pergi.
c. Dia ingin cepat-cepat pergi sebenarnya.
(7) a. Biasanya dia pulang sebelum magrib.
b. Dia biasanya pulang sebelum magrib.
c. Dia pulang sebelum magrib biasanya.
Pada tataran klausa, adverbia yang merupakan pewatas verba,
adjektiva, atau adverbia lain menjelaskan kata atau bagian kalimat yang pada
umumnya berfungsi sebagai predikat. Fungsi sebagai predikat ini bukan
satu-satunya ciri untuk menentukan adverbia karena adverbia juga dapat
menerangkan kata atau bagian kalimat yang tidak berfungsi sebagai predikat.
Itulah sebabnya ada sejumlah adverbia yang, selain dapat menerangkan
verba, adjektiva, atau adverbia lain, juga dapat menerangkan nomina dan
frasa preposisional.
Karena pronomina dan numeralia dari segi kategori sangat erat
berkaitan dengan nomina, adverbia pun dapat mewatasi atau men
jelaskan pronomina atau numeralia.
Contoh:
(8) a. Anak yang terpandai saja tidak dapat menjawab pertanyaan itu.
b. la menyanyikan lagu keroncong hampir sepuluh buah.
c. Yohana berjualan batik sutra saja.
d. A: "Kau suka nyanyi?"
B: "Ya, tapi hanya di kamar mandi."
Pada contoh di atas adverbia saja menjelaskan anak yang terpandai
yang berfungsi sebagai subjek; adverbia hampir menjelaskan sepuluh lagu
keroncong yang berfungsi sebagai objek; adverbia saja menjelaskan batik
sutra yang berfungsi sebagai pelengkap; sedangkan di kamar mandiy yang
merupakan keterangan, dijelaskan oleh adverbia hanya.
Jika dilihat dari segi kategorinya, anak yang terpandai merupakan frasa
nominal, sepuluh buah merupakan frasa numeral, sedangkan di kamar mandi
merupakan frasa preposisional. Dengan demikian, yang dapat dijadikan
patokan sebagai ciri adverbia bukan hanya fungsi kata atau bagian kalimat
yang diterangkan, melainkan juga kategorinya.
Contoh:
(9) a. Jika dilihat dari penampilannya, dia pasti seorang guru.
b. Yang dapat menghibur hatinya hanya kamu.
c. Anaknya baru satu.
d. Kalau hari libur, ia selalu di rumah.
Pada contoh di atas terlihat bahwa adverbia pasti menjelaskan frasa
nominal seoranggurUy adverbia hanya menjelaskan pronomina persona kamu,
adverbia baru menjelaskan numeralia satu, dan adverbia selalu menjelaskan
frasa preposisional di rumah. Jika dilihat dari fungsi sintaktisnya, bagian
kalimat yang dijelaskan adverbia pada keempat contoh tersebut merupakan
predikat.
Mengenai fungsi sintaktis ini, khususnya yang menyangkut contoh
(9d), dapat dijelaskan sebagai berikut.
a) Bentuk selalu di rumah mempunyai makna yang sama dengan selalu
{ber)ada di rumah.
b) Adverbia selalu merupakan bagian dari frasa preposisional selalu di
rumah\ yang dijelaskannya ialah makna kata ada yang terkandung
dalam frasa preposisional di rumah.
Walaupun adverbia dapat menerangkan fungsi subjek, peran adverbia
tertentu sebagai penjelas subjek sering kali diragukan. Kalimat Semua petani
menanam jagungXthih. lazim daripada kalimat Hanyapetani menanam jagung.
Nomina petani yang dijelaskan oleh numeralia semua pada contoh pertama
jelas berfungsi sebagai subjek. Akan tetapi, nomina petani yang dijelaskan
oleh adverbia hanya pada contoh kedua diragukan fungsinya sebagai subjek.
Contoh;
(10) a. {Hanya) petani menanam jagung.
b. Hanya petani yang menanam jagung.
c. Yang menanam jagung hanya petani.
Dalam ragam formal contoh (10a) dianggap berasal dari (10b)
melalui penghilangan kata m^OLsyang, sedangkan (10b) itu berasal dari (10c).
Berdasarkan ^xxn^smyz, yang menanam jagung p2id2i (10b—10c) merupakan
subjek dan hanya petani sebagai predikat. Perubahan (10c) menjadi (10b)
terjadi melalui pemfokusan predikat. Perubahan seperti itu lazim disebut
inversi.
6.2 ADVERBIA DARI SEGI PERILAKU SEMANTISNYA
Berdasarkan perilaku semantisnya, dapat dibedakan delapan jenis adverbia,
yaitu (1) adverbia kualitatif, (2) adverbia kuantitatif, (3) adverbia iimitatif,
(4) adverbia frekuentatif, (5) adverbia kewaktuan, (6) adverbia kecaraan, (7)
adverbia kontrastif, dan (8) adverbia keniscayaan.
6.2.1 Adverbia Kualitatif
Adverbia kualitatif adalah adverbia yang menyatakan makna yang
berhubungan dengan tingkat, derajat, atau mutu. Yang termasuk adverbia
ini, antara lain, adalah paling, sangat, lebih, agak, dan kurang.
Contoh;
(11) a. Saya paling suka masakan Sunda.
b. Senyumnya sangat menggemaskan.
c. Ujiannya lebih sulit daripada yang kuduga.
d. Permainannya kurang sempurna.
e. Lin Dan agak kerepotan mengembalikan smes Taufik.
6.2.2 Adverbia Kuantitatif
Adverbia kuantitatif adalah adverbia yang menyatakan makna yang
berhubungan dengan jumlah. Yang termasuk adverbia ini, antara lain, adalah
banyak, sedikit, kira-kira, dan cukup.
Contoh:
(12) a. Lukanya mengeluarkan darah.
b. Penghasilannya sekarang sedikit berkurang jika
dibandlngkan dengan sebelumnya.
c. Setiap hari dia memerlukan uang belanja kira-kira
seratus ribu rupiah.
d. Gaji bulanannya hanya cukup untuk hidup seminggu.
6.2.3 Adverbia Limitatif
Adverbia limitatif adalah adverbia yang menyatakan makna yang berhubungan
dengan pembatasan. Yang termasuk adverbia ini, antara lain, adalah hanya,
saja, dan sekadarContoh:
(13) a. Ohdii \t\i hanya n\cn^2imh2LX. pertumbuhan penyakit.
b. Kami di rumah saja selama liburan ini.
c. la sekadar mencoba menarik hatiku.
Adverbia hanya pada (13a) membatasi berbagai dampak obat itu
pada menghambat penyakit ('tidak menyembuhkan penyakit').
Adverbia saja pada (13b) membatasi kegiatan subjek kami pada {tinggal) di
rumah selama liburan. Adverbia sekadar pada (13c) membatasi kegiatan
subjek ia pada mencoba menarik hatiku ('tidak untuk menjadi calon istrinya').
6.2.4 Adverbia Frekuentatif
Adverbia frekuentatif adalah adverbia yang menyatakan makna yang
berhubungan dengan tingkat kekerapan terjadinya sesuatu yang diterangkan
oleh adverbia itu. Yang termasuk adverbia ini, antara lain, adalah selalu,
sering, jarang, dan kadang-kadang.
Contoh:
(14) a. Kami selalu makan malam bersama-sama.
b. Mereka sering mengabaikan tanggung jawabnya.
c. Para siswa yang rajinyVzmw^ dnggal kelas.
d. Kadang-kadang say^ terkejut dengan usulnya yang tidak terduga.
6.2.5 Adverbia Kewaktuan
Adverbia kewaktuan adalah adverbia yang menyatakan makna yang ber
hubungan dengan saat terjadinya peristiwa yang diterangkan oleh adverbia.
Yang termasuk adverbia ini, antara lain, adalah baru, segera, langsung, dan
lekas
Contoh:
(15) a. Ayah barn diberhentikan dari jabatannya.
b. Kami berlima akan segera membicarakan masalah itu.
c. Dia langsung pergi setelah mendengar berita itu.
d. Semoga pekerjaan itu lekas selesai.
6.2.6 Adverbia Kecaraan
Adverbia kecaraan adalah adverbia yang menyatakan makna yang berhubungan
dengan cara terjadinya peristiwa yang diterangkan oleh adverbia. Yang
termasuk adverbia ini, antara Iain, adalah diam-diam, secepatnya, dan pelanpelan.
Contoh:
(16) a. Ikuti dia diam-diam dari belakang!
b. Kami akan menyelesaikan tugas itu secepatnya.
c. Pelan-pelan la membuka pintu kamar itu.
6.2.7 Adverbia Kontrastif
Adverbia kontrastif adalah adverbia yang menyatakan pertentangan dengan
makna kata atau hal yang dinyatakan sebelumnya. Yang termasuk adverbia
kontrastif ini, antara lain, adalah bahkan, malahan, dsinjustru.
Contoh:
(17) a. Saya tidak pernah ke rumahnya, bahkan sampai sekarang
alamatnya pun saya tidak tahu.
b. Jangankan saya diberi ongkos pulang, dia malahan mau
pinjam uang dari saya.
c. Siapa bilang dia kikir,y«r/rM dia yang menyumbang paling
banyak.
6.2.8 Adverbia Keniscayaan
Adverbia keniscayaan adalah adverbia yang menyatakan makna yang
berhubungan dengan kepastian tentang keberlangsungan atau terjadinya hal
atau peristiwa yang diterangkan adverbia. Yang termasuk adverbia ini, antara
lain, adalah niscaya, pasti, dan tentu.
Contoh:
(18) a. Niscaya manusia akan hancur jika mengabaikan hal itu.
b. Kami pasti akan menemukannya nanti.
c. Pemerintah tentu akan memperhatikan semua usul yang
disampaikan para wakil rakyat.
6.3 ADVERBIA DARI SEGI PERILAKU SINTAKTISNYA
Perilaku sintaktis adverbia dapat dilihat berdasarkan posisinya terhadap kata
atau bagian kalimat yang dijelaskan oleh adverbia yang bersangkutan. Atas
dasar itu, dapat dibedakan enam macam posisi adverbia sebagai berikut:
a) Adverbia yang digunakan sebelum kata yang diterangkan;
b) Adverbia yang digunakan setelah kata yang diterangkan;
c) Adverbia yang digunakan sebelum atau sesudah kata yang diterangkan;
d) Adverbia yang digunakan sebelum dan sesudah kata yang diterangkan;
e) Adverbia pembuka wacana;
f) Adverbia intraklausal dan ekstraklausal.
6.3.1 Adverbia Sebelum Kata yang Diterangkan
Dalam struktur kalimat, adverbia ini digunakan sebelum, atau mendahului,
kata yang diterangkan.
Contoh:
(19) baru\\x\\xs
hanya sedikit
jarang datang
lebih tinggi
selalu hadir
paling raj in
sering mogok
sangat pandai
terlalu sulit
(20) a. la lebih tinggi daripada adiknya.
b. Telaga itu sangat indah.
c. Pendiriannya terlalu kukuh untuk digoyahkan,
d. Kami hanya menulis apa yang dikatakannya.
e. Murid yang paling plntar mendapat hadiah dari sekolahnya.
6.3.2 Adverbia Sesudah Kata yang Diterangkan
Dalam struktur kalimat, adverbia ini digunakan setelah, atau mengikuti,
kata yang diterangkan.
Contoh:
(21) cantik benar
datangyW
panclai^«^^
indah nian
baru saja
baik pula
satu pun
pen ting sekali
a. Tampan nian teman barumu.
b. Kami duduk-duduk saja menunggu panggilan.
c. Mahal benar harganya.
d. Warna baju yang dikenakannya mencolok sekali.
e. Karena semua buruh ikut berunjuk rasa, pabrik pun diliburkan.
6.3.3 Adverbia Sebelum atau Sesudab Kata yang Diterangkan
Adverbia jenis ini dapat digunakan sebelum ataupun sesudah kata yang
(22)
diterangkan.
Contoh:
(23) amat baik
kembali datang
segera pulang
terus jalan
baik amat
datang kembali
pulang segera
jalan terus
(24) a.
b.
c.
. Kini barang-barang elektronik amat mahal harganya.
i. Mahal tfwtf^harga barang-barang itu.
Paginya ia segera pergi meninggalkan kami.
i. Begitu mendengar berita itu, ia pergi segera.
la terus bekerja menyelesaikan tugas untuk besok.
i. la bekerja terus menyelesaikan tugas untuk besok.
6.3.4 Adverbia Sebelum dan Sesudah Kata yang Diterangkan
Telah dikemukakan bahwa ada jenis adverbia yang dapat digunakan sebelum
atau sesudah kata yang diterangkan (lihat 6.3.3). Sementara itu, ada adverbia
yang terdiri atas dua kata yang digunakan sebelum dan sesudah kata yangditerangkan. Dengan demikian, jenis adverbia yang dimaksudkan tergolong
adverbia gabungan yang tidak berdampingan (lihat 6.4.2.2).
Contoh:
(25) bukan ... saja
hanya ... saja
sangat... sekali
belum ... juga
(26) a. Saya yakin bukan dia saja yang pandai.
b. Bagiku, senyumannya sangat manis sekali.
c. Kami hanya menerima saja apa yang diberikannya.
d. Meskipun sudah belajar slang dan malam, dla belum
\\A\xs juga.
Adverbia gabungan sangat... sekali seperti pada (26b) dan hanya ...
saja seperti pada (26c) sering digunakan dalam ragam tidak formal.
6.3.5 Adverbia Pembuka Wacana
Adverbia jenis ini digunakan untuk mengawali suatu wacana atau
paragraf. Penggunaannya didasarkan pada makna yang terkandung
pada paragraf sebelumnya. Dalam bahasa Indonesia perlu dibedakan antara adverbia pembuka wacana yang masih sering dipakai (27a) dan
adverbia pembuka wacana yang umumnya hanya terdapat pada naskah sastra
lama (27b).
Contoh:
(27) a. adapun
akan ha!
dalam pada itu
sementara itu
sehubungan dengan hal tersebut
b. alkisah
arkian
syahdan
hatta
kalakian
(28) Adapun permasalahannya sekarang ialah apakah memang sudah ada
tokoh dari generasi muda yang benar-benar sudah layak diajukan sebagai
capres pada pemilu 2014.
(29) Akan /?/2/lamarannya menjadi salah seorang guru di Sekolah Dasar Inpres
Raya ini telah kami bicarakan dalam rapat guru minggu yang lalu; dalam
waktu dekat ia akan mengetahui hasilnya direrima atau dicolak.
(30) Dalam pada itu, para pemuda desa ini mendukung saya karena saya ingin
beternak lebah dan menanam jamur. Mereka yakin upaya dan usaha saya
akan berhasil sehingga ingin menuruti jejak saya.
(31) Alkisah, pada masa dulu memerintahlah seorang raja yang arif bijaksana
di daerah ini.
(32) Arkian, baginda raja yang arif bijaksana itu mempunyai tujuh orang
putri yang cantik jelita yang tidak ada bandingnya di kerajaan itu.
(33) Syahdan, pada suatu hari datanglah ke istana raja seorang lelaki tua
yang bungkuk dan sangat mengerikan dan mengemukakan niat untuk
melamar puteri raja menjadi isterinya.
(34) Sebermula, pada zaman dahulu itu datanglah malapetaka yang dahsyat
yang memusnahkan penduduk daerah ini dengan air bah yang ganas.
Setelah itu, orang menamai daerah itu Kalenglengen yang bermakna
'tenggelam' atau 'terbenam'. Begitulah ceritanya asal mula nama desa itu
menjadi Desa Kalenglengan.
(35) KalakiaUy setelah sedikit hari kemudian daripada itu kedengaranlah
berita keberangkatannya ke Malaka.
(36) Hatta, baginda pun bergetarlah hatinya mendengar kata istrinya itu.
Kata-kata arkian, syahdan, sebermula, kalakian, dan hatta saat ini
telah menjadi bentuk arkais.
6.3.6 Adverbia Intraklausal dan Ekstraklausal
Seperti telah dikemukakan pada awal bab ini, ciri utama adverbia ialah
fungsinya sebagai pewatas, balk sebagai pewatas verba, pewatas adjektiva
maupun pewatas kalimat (lihat 6.1). Perilaku sintaktis adverbia pada kalimatkalimat yang telah dicontohkan pada 6.4.1-6.4.2,2 memperlihatkan bahwa,
dari segi lingkup strukturnya, yang diterangkan atau dijelaskan oleh adverbia
itu terbatas pada satuan atau tataran frasa saja. Selain itu, ada pula adverbia
yang menerangkan satuan atau tataran yang lebih tinggi, yaitu yang berupa
klausa atau kalimat.
Yang terikat pada satuan atau tataran frasa ialah adverbia yang
digunakan sebagai pewatas verba atau pewatas adjektiva. Sementara itu, yang
menerangkan satuan atau tataran yang lebih tinggi dari frasa ialah adverbia
yang digunakan sebagai pewatas kalimat.
Contoh:
(37) a. Dia sudah makan di rumah temannya.
b. Saudara sepupu saya sangat ramah.
c. Mereka masih tetap tinggal bersama orang tuanya.
(38) a. i. Seharusnya dia datang sebelum pukul delapan.
ii. Dia seharusnya datang sebelum pukul delapan.
iii. Dia datang sebelum pukul delapan seharusnya.
. Agaknya penjelasan pejabat Itu tidak mereka pahami.
i. Penjelasan pejabat itu agaknya tidak mereka pahami.
ii. Penjelasan pejabat itu tidak mereka pahami agaknya.
c. Sebaiknya Saudara tidak usah datang.
1. Saudara sebaiknya tidak usah datang.
ii. Saudara tidak usah datang sebaiknya.
Penggunaan adverbia yang terikat pada tataran frasa terlihat pada
contoh (37), sedangkan yang terikat pada tataran klausa atau kalimat
dicontohkan pada (38). Adverbia sudah, sangat, dan masih pada (37) masingmasing menerangkan verba makan, adjektiva ramah, dan frasa verbal tetap
tinggal. Baik sudah makan, sangat ramah maupun masih tetap tinggal ketigatiganya merupakan satuan pada tataran frasa yang berfungsi sebagai predikat.
Pada contoh (38) seharusnya, agaknya, dansebaiknya tidak memberikan
keterangan pada predikat kalimat yang bersangkutan, tetapi pada seluruh
kalimat. Dengan demikian, seharusnya pada (38a) mewatasi klausa Dia
datang sebelum pukul delapan, agaknya pada (38b) mewatasi klausa Penjelasan
pejabat itu tidak mereka pahami, dan sebaiknya pada (38c) mewatasi klausa
Saudara tidak usah datang.
Berdasarkan lingkup strukturnya itu, terdapat perbedaan antara
pewatas pada tataran frasa dan pewatas pada tataran klausa. Pewatas pada
tataran frasa merupakan adverbia intraklausal, sedangkan pewatas yang
mengacu pada tataran klausa merupakan adverbia ekstraklausal.
Yang perlu diperhatikan sehubungan dengan perbedaan itu ialah
unsur atau bagian kalimat yang diterangkan oleh adverbia yang bersangkutan.
Adverbia intraklausal mewatasi frasa dan adverbia ekstraklausal mewatasi
klausa. Pada contoh (39) berikut terlihat bahwa benar-benar^ meskipun dalam
posisi sintaktis yang berbeda-beda, tetap mewatasi verba memperhatikan.
Tidaklah demikian halnya dengan sebenarnya pada contoh (38) (40).
Adverbia sebenarnya, baik digunakan di awal, di tengah, maupun di akhir
kalimat, tetap merupakan pewatas pada klausa Dia termasuk murid yang
pandai.
Contoh:
(39) a. Dia benar-benar memperhatikan nasihat orang tuanya.
b. Dia memperhatikan nasihat orang tuanya benar-benar.
c. Benar-benar dia memperhatikan nasihat orang tuanya.
(40) a. Sebenarnya dia termasuk murid yang pandai.
b. Dia sebenarnya termasuk murid yang pandai.
c. Dia termasuk murid yang pandai sebenarnya.
6.4 ADVERBIA DARI SEGI BENTUKNYA
Dari segi bentuknya, adverbia tunggal perlu dibedakan dari adverbia
gabungan. Adverbia tunggal dapat diperinci menjadi (1) adverbia yang
berupa kata dasar, (2) adverbia yang berupa kata berafiks, dan (3) adverbia
yang berupa kata ulang. Adverbia gabungan dibedakan menjadi (1) adverbia
gabungan yang berdampingan dan (2) adverbia gabungan yang tidak
berdampingan.
6.4,1 Adverbia Tunggal
Seperti sudah disebutkan, adverbia tunggal dapat dibedakan menjadi tiga
macam, yaitu adverbia yang berupa (a) kata dasar, (b) kata berafiks, dan (c)
kata ulang.
6.4.1.1 Adverbia Berupa Kata Dasar
Adverbia yang berupa kata dasar hanya terdiri atas satu morfem. Karena
jenis adverbia dasar tergolong ke dalam kelompok kata yang keanggotaannya
tertutup, jumlah adverbia yang berupa kata dasar itu tidak banyak, termasuk
di dalamnya pemarkah negasi {tidak^ bukan), pemarkah keaspekan (seperti
akan, sedang, dan sudah), pemarkah modalitas (seperti ingin, man,perlu, dan
harus), pemarkah kualitas (seperti agak, cukup, dan sangat), dan pemarkah
pembandingan [lehih, kurang, dan paling.
Contoh:
(41) akan hanya mungkin segera
amat harus nian sempat
bahkan hendak niscaya sekali
barangkali ingin paling selalu
baru jarang pastl senantiasa
belum jua patut sering
benar juga perlu sudah
bisa justru mesti sedang
boleh kembali sungguh telah
bukan kurang pernah tengah
cukup lagi pula tentu
cuma lebih pun terus
dapat malah saja tidak
hampir mau sangat wajib
Sehubungan dengan senarai adverbia di atas, perlu dikemukakan
catatan mengenai keanggotaan ganda. Kata baru, misalnya, selain sebagai
adverbia, dapat juga digolongkan sebagai adjektiva. Pada contoh kalimat Dia
baru membelt mobil baruy kata baru sebeium membeli merupakan adverbia,
sedangkan kata baru setelah mobil adalah adjektiva.
6.4.1.2 Adverbia Bempa Kata Beraiiks
Adverbia yang berupa kata berafiks diperoleh dengan menambahkan gabungan afiks se-...'nya atau afiks -nya pada kata dasar.
1) Yang berupa penambahan gabungan afiks se-...'nya pada kata dasar
Contoh:
(42) sebaiknya
sesungguhnya
sebenarnya
sebetulnya
seharusnya
sejatinya
seyogianya
selayaknya
semestinya
sepatutnya
(43) a. Sebaiknya kita segera membayarkan pajak itu.
b. Sebenarnya kami meragukan kemampuannya.
c. Dia sepatutnya berterima kasih kepada orang yang telah
menoiongnya.
d. Mereka sesungguhnya tidak bersalah.
2) Yang berupa penambahan -nya pada kata dasar
Contoh:
(44) agaknya
biasanya
khususnya
kiranya
lazimnya
malangnya
mestinya
nyatanya
rupanya
sayangnya
tampaknya
untungnya
pokoknya
umumnya
rasanya
(45) a. Agaknya gurauan itu membuatnya marah.
b. Kalau sudah begitu, biasanya ia akan menangis.
c. Kamu ini pintar juga rupanya.
d. Rasanya saya sudah melaporkannya kemarin.
Di dalam bahasa Indonesia terdapat juga adverbia berafiks
yang dllihat dari segi bentuknya tidak termasuk ke dalam salah satu
pola tersebut. Yang dimaksudkan adalah terlalu., terlampau^ dan terkadang. Pola yang memperlihatkan penambahan prefiks ter- pada kata
dasar ini hanya berlaku untuk ketiga adverbia itu. Namun, dalam konteks
pemakaian tertentu kadang-kadang digunakan bentuk teramat yang juga
merupakan adverbia.
6.4.1.3 Adverbia Berupa Kata Ulang
Menurut bentuknya adverbia yang berupa kata ulang dapat diperinci lagi
menjadi empat macam, yaitu (a) pengulangan kata dasar, (b) pengulangan
kata dasar dan penambahan afiks se-, (c) pengulangan kata dasar dan
penambahan sufiks -an, dan (d) pengulangan kata dasar dan penambahan
gabungan afiks se-...-nya. Bentuk-bentuk adverbia yang berupa kata ulang
tersebut dapat dicontohkan sebagai berikut.
1) Adverbia yang berupa pengulangan kata dasar
Contoh:
(46) belum-belum
diam-diam
jarang-jarang
kadang-kadang
kira-kira
lagi-lagi
lekas-lekas
mula-mula
pelan-pelan
sering-sering
malam-malam
tiba-tiba
(47) a. Kami duduk diam-diam mendengarkan ceramah.
b. Lekas-lekas dia berdiri meninggalkan kami.
c. Anak itu pelan-pelan membuka matanya.
d. Mula-mula kami merasa takut kepadanya.
2) Adverbia yang berupa pengulangan kata dasar dengan penambahan
prefiks seContoh:
(48) secepat-cepat
sedekat-dekat
sejauh-jauh
setinggi-tinggi
sekuat-kuat
sejelek-jelek
sekeras-keras
sepandai-pandai
sesabar-sabar
(49) a. Setinggi-tinggi bangau terbang, jatuhnya ke kubangan juga.
b. Sepandai-pandai guru, ia tidak boieh meremehkan muridnya.
c. Sesabar-sabar manusia tentu ada batasnya.
d. Segalak-galak macan tidak akan memangsa anaknya
sendiri
3) Adverbia yang berupa pengulangan kata dasar dengan penambahan sufiks
-an
Contoh:
(50) besar-besaran
gelap-gelapan
gila-gilaan
habis-habisan
kecil-kecilan
mabuk-mabukan
mati-matian
terang-terangan
(51) a. mcmdiVzWrnyz habis-habisan V&mzvxn.
b. la berjuang mati-matian melawan penyakit itu.
c. Kalian dapat berdagang kecil-kecilan di desa.
d. Gila-gilaan ia memacu motornya.
4) Adverbia yang berupa pengulangan kata dasar dengan penambahan
gabungan afiks se-...-nya
Contoh:
(52) sebanyak-banyaknya
secepat-cepatnya
sedalam-dalamnya
sehalus-halusnya
seikhlas-ikhlasnya
sekecil-kecilnya
sekeras-kerasnya
sekuat-kuatnya
sekurang-kurangnya
selambat-lambatnya
seluas-luasnya
sepuas-puasnya
serajin-rajinnya
setlnggi-tingginya
setulus-tulusnya
271/595
(53) a. ^nrnn^xm terbang setinggi-tingginya.
b. Kami turut berduka sedalam-dalamnya.
c. Saya menyumbang seikhlas-ikhlasnya.
d. Kami menarik tali itu sekuat-kuatnya.
Perhatikan bahwa pada bentuk ulang dengan se-^ -an^ dan sebentuk dasar yang mengalami pengulangan itu tergolong adjektiva.
.-nyUy
6.4.2 Adverbia Gabungan
Adverbia gabungan terdiri atas dua adverbia yang berupa kata dasar. Kedua
kata dasar yang merupakan adverbia gabungan itu ada yang berdampingan
dan ada yang tidak berdampingan. Ada juga adverbia gabungan yang terdiri
atas tiga kata dasar, tetapi jumlahnya sedikit sekali.
6.4.2.1 Adverbia Gabungan yang Berdampingan
Yang dimaksud dengan adverbia gabungan yang berdampingan ialah dua
adverbia (atau lebih) yang posisi sintaktisnya berdampingan tanpa ada kata
yang mengantarainya.
Contoh:
(54) tidak saja lebih kurang akan segera
bukan saja tidak lagi harus segera
tentu saja tidak akan ingin segera
hampir saja sudah akan tidak harus
baru saja baru akan belum harus
hanya saja bukan hanya sudah harus
selalu saja tidak hanya tidak akan pernah
akan selalu belum pernah hampir tidak pernah
hampir selalu sudah pernah mau tidak mau
tidak selalu tidak pernah paling tidak
(55) a. Wakru kami datang, dia baru saja pergi.
b. Tentu saja dia tidak man pergi karena belum diberi ongkos.
c. Cuaca mendung tidak selalu berarti akan turun hujan.
d. Ibunya harus segera dibawa ke dokter.
e. Selama lima tahun bekerja, dia belum pernah mendapat
kenaikan gaji.
f. Akibat ulahnya, tidak hanya dia sendiri yang menanggung
malu, keiuarganya juga.
g. Pak Sastro masih belum pulang, padahai istrinya ulang tahun.
h. Pejabat baru itu berjanji tidak akan pernah melakukan
korupsi arau menerima suap.
6.4.2.2 Adverbia Gabimgan yang Tidak Berdampingan
Adverbia gabungan yang tidak berdampingan adalah dua adverbia (atau
lebih) yang dipisahkan oleh unsur kallmat yang lain.
Contoh:
(56) bukan ... saja
sudah ... kembali
telah... kembali
tidak ... juga
belum ... juga
belum ... lagi
tidak ... lagi
sudah ... lagi
(57) a. Yang dapat melakukan pekerjaan itu bukan mereka saja.
b. Karena disiplin dalam menjaga pola makannya, kesehatannya
sudah pulih kembali.
c. Dia tidak ]cs2ijuga meskipun telah jatuh berkali-kali.
d. Dia sudah berobat ke mana-mana, tetapi penyakitnya belum
sembuhy«g«.
e. Dia tidak tinggal di Bogor lagi karena bekerja di Serang.
Selain yang telah dikemukakan, yaitu adverbia gabungan yang
berdampingan dan yang tidak berdampingan, ada pula beberapa adverbia
gabungan yang dapat digunakan, balk secara berdampingan maupun tidak
berdampingan.
Contoh:
(58) a. i. Dia tidak lagi tinggal di sini.
ii. Dia tidak tinggal di sini lagi.
b. 1. Sudah dua jam menunggu, dia belumjuga datang.
ii. Sudah dua jam menunggu, dia belum dzxdtn^juga.
c. 1 Karena sudah tidak tahan lagi, dia ingin segera minta
berhenti.
ii. Karena sudah tidak tahan lagi, dia ingin minta berhenti
segera.
6.5 BENTUK ADVERBIAL
Paparan tentang pewatas verba, pewatas adjektiva, atau pewatas adverbia lain,
sebagaimana telah dipaparkan pada 6.1, merupakan salah satu ciri adverbia.
Selain itu, ada satu ciri lagi yang sering disebut adverbial. Perbedaannya ialah bahwa adverbia merupakan salah satu kategori gramatikal atau kelas kata,
sedangkan adverbial merupakan salah satu fungsi sintaktis.
Dalam konteks kalimat, adverbial dapat berupa nomina atau frasa
nominal, verba atau frasa verbal, adjektiva atau frasa adjektival, atau frasa
preposisional.
1) Nomina sebagai Adverbial
Contoh:
(59) a. Sekarang paman saya tlnggal di Bandung.
b. Hari ini dia tidak masuk kantor.
c. Dia harus bekerja siang dan malam untuk menghidupi
keluarganya.
d. Kemarin saya tidak pergi ke mana-mana.
2) Adjektiva sebagai Adverbial
Contoh:
(60) a. Angin bertiup kencang.
b. Dia berjuang keras untuk mencapai cita-citanya.
c. Anak raj in itu tekun belajar.
d. Wanita itu menangis sedih karena anaknya tidak lulus
ujian.
3) Frasa Preposisional sebagai Adverbial
Contoh:
(61) a. Kami sekeluarga berlibur di Puncak.
b. Dia membawa hadiah untuk teman-temannya.
c. Dia menerima ancaman dari seseorangyang tidak dikenalnya.
d. Dia pergi naik haji bersama istri dan dua orang anaknya.
Adverbial atau keterangan ini dipaparkan lebih lanjut pada bagian
tentang kalimat (lihat 9.3.2.5).
6.6 ADVERBIA DAN KELAS KATA LAIN
Pada 6.4 telah disebutkan bahwa dilihat dari segi bentuknya, salah satu jenis
adverbia adalah adverbia tunggal. Selain dasar yang berkategori adverbia
(misalnya hampir menjadi hampir-hampir), bentuk dasar adverbia tunggal
dapat pula berupa verba, adjektiva, nomina, dan numeralia. Berdasarkan
kategori bentuk dasarnya itu, adverbia tunggal dapat berupa adverbia deverbal,
adverbia deadjektival, adverbia denominal, dan adverbia denumeral.
6.6.1 Adverbia Deverbal
Adverbia deverbal adalah adverbia yang dibentuk dari dasar yang berkategori
verba. Pada contoh berikut adverbia kira-kira, sekiranya, terlalu, dan tahutahu masing-masing diiurunkan dari verba kira, lalu, dan tahu.
Contoh:
(62) a. la akan datang kira-kira pukul sepuluh.
b. Lupakan saja apa yang pernah saya usulkan sekiranya hal itu
mengganggu.
c. Terlalu dini untuk menerima usulannya.
d. Tahu-tahu saya didatangi oleh petugas pajak.
6.6.2 Adverbia Deadjektival
Adverbia deadjektival adalah adverbia yang dibentuk dari adjektiva, baik
melalui reduplikasi maupun afiksasi. Adverbia diam-diam, sebaiknya,
sebenamya, dan setinggi-tingginya masing-masing diturunkan dari dasar
dianiy baiky benary dan tinggi yang berkategori adjektiva.
Contoh:
(63) a. Komplotan itu diam-diam menyelundupkan barang haram
lewat pelabuhan.
b. Sebaiknya kalian sendiri yang harus menyelesaikan
permasalahan itu.
c. Masalah itu sebenamya ringan sekali.
d. la didenda setinggi-tingginya lima juta rupiah.
6.6.3 Adverbia Denominal
Adverbia denominal adalah adverbia yang dibentuk dari dasar yang
berkategori nomina. Adverbia rupanyuy agaknyUy dan malam-malam pada
contoh berikut, misalnya, diturunkan dari kata rupUy agaky dan malam yang
berkategori nomina.
Contoh:
(64) a. Rupanya ia ingin memperkenalkan kami dalam pertemuan itu.
b. Agaknya cara itulah yang tepat untuk mengimbangi kritlkan
mereka.
c. Mereka menggedor pintuku malam-malam
6.6.4 Adverbia Denumeral
Seperti halnya nomina, numeralia dapat juga menjadi dasar pembentukan adverbia. Pada contoh berikut adverbia dua-duUy setengah-setengahy
dan sedikit'sedikit masing-masing diturunkan dari numeralia duUy setengahy
dan sedikit.
Contoh:
(65) a. Masukkan bungkusan itu dua-dua.
b. Kalau bekerja, jangan setengah-setengah.
c. Sedikit-sedikit mereka mengadu ke DPR.
Pembahasan dalam bab ini mencakup nomina (7.1), pronomina (7.2), dan
numeralia (7.3). Ketiga kelas kata itu berhubiingan erat dalam pemakaian.
Pronomina dipakai untuk menggantikan nomina atau frasa nominal dalam
kalimac dan numeralia biasanya hadir dalam kalimat bersama nomina.
7.1 NOMINA
7.1.1 Batasan dan Ciri Nomina
Nomina dapat dikenali dan dibedakan dari kelas kata yang lain dengan
mengamati (1) perilaku semantis, (2) perilaku sintaktis, dan (3) bentuk
morfologisnya. Dari segi semantis, nomina adalali kata yang mengacu pada
manusia, binatang, benda, dan konsep atau pengertian. Kata anak, kuda, dan
air termasuk nomina yang masing-masing mengacu pada manusia^ binatang,
dan benda. Ketiga kata itu tergolong nomina konkret. Sebaliknya, kata-kata,
seperti waktu, cinta, kesedihan, dan kemanusiaan termasuk nomina abstrak
yang mengacu pada konsep atau pengertian. Kata-kata yang disebutkan di
atas tergolong nomina umum. Acuannya berubah-ubah bergantung pada
kapan, di mana, dan siapa yang menggunakannya. Selain nomina umum,
ada nomina yang acuannya spesifik dalam arti relatif tidak berubah, seperti
Andi, Depok, Badan Bahasa, dan Indonesia. Kata-kata jenis itu lazim disebuc
nama diri.
Dari segi sintaktis, nomina dapat dikenali dengan mengamati ciri-ciri
berikut.
1) Nomina atau frasa nominal, dengan atau tanpa pewatas, umumnya
terletak di awal kalimat sebagai subjek. Fungsi subjek itu umumnya
diduduki oleh nomina atau frasa nominal.
Contoh:
(1) Anak itu sedang tidur.
(2) Polisi belum menerima laporan penculikan itu.
(3) Perempuan itu berjualan pakaian bekas.
(4) Andi murid terpandai di sekolah itu.
Bentuk anak itu, polisi, perempuan itu, dan Andi yang terletak di
awal kalimat pada contoh (1)—(4) merupakan nomina atau frasa nominal
yang menduduki fungsi subjek. Kata itu pada anak itu dan perempuan itu
merupakan pewatas nomina yang mengikutinya.
2) Nomina, sebagai inti frasa, dapat diikuti kelas kata lain seperti adjektiva,
verba, numeralia, atau frasa preposisional yang diantarai atau dapat diantarai oleh kata sebagai ligatur (perangkai).
Contoh:
(5) rumah besar — rumah yang besar
pakaian dibeli — pakaian yang dibeli
hari ketiga — hari yang ketiga
buku di meja — buku yang di meja
Kehadiran yang pada frasa nominal yang pewatasnya verba atau frasa verbal
cenderung bersifat wajib. Jika yang tidak hadir, verba itu cenderung akan
ditafsirkan sebagai predikat kalimat. Kehadiran yang dalam konstruksi pa
kaian yang dibeli dapat ditafsirkan sebagai kalimat berpola predikat-subjek.
3) Nomina sebagai inti frasa juga dapat diikuti oleh kata penunjuk ini atau
itu, baik secara langsung maupun dengan diantarai oleh kata lain.
Contoh:
(6) kota ini — kota besar ini
orang ini orang kaya ini
anak itu — anak (yang) di pojok itu
pekerjaan itu — pekerjaan rumah itu
4) Nomina tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak. Kata pengingkarnya
ialah bukan. Pengingkaran terhadap kalimat Ayah saya guru adalah Ayah
saya bukan guru.
7.1.2 Nomina dari Segi Perilaku Semantisnya
Pada dasarnya tiap kata, termasuk nomina, yang mempunyai makna
leksikal akan memiliki sejumlah komponen makna atau fitur semantis
yang terkandung pada kata itu. Di antara fitur-fitur semantis itu ada yang
sifatnya kodrati dan ada yang sifatnya budaya. Ciri yang kodrati bersifat
universal. Makna yang dalam bahasa Indonesia disebut 'kuda' dalam bahasa
mana pun akan memiliki fitur-fitur semantis kodrati yang sama, misalnya,
kakinya empat, matanya dua, dan warnanya ada yang hitam, putih, cokelat,
atau abu-abu. Jika ada kelompok masyarakat yang memahami makna kuda
sebagai makanan, fitur makanan pada makna kuda bersifat budaya.
Fitur semantis, terutama yang bersifat kodrati, memegang peranan
penting dalam bahasa. Kehadiran dua kata atau lebih dalam kalimat menuntut
adanya keserasian fitur semantis antara kata-kata itu. Ketidakserasian fitur
semantis cenderung akan menimbulkan keganjilan seperti terlihat pada
contoh berikut.
(7) a. Kuda saya hitam.
b. *Kuda saya hijau.
Kalimat (7a) berterima, tetapi kalimat (7b) terasa aneh karena fitur
semantis hijau tidak lazim pada kuda. Warna kuda hanya bisa hitam, putih,
cokelat, atau abu-abu (dan mungkin juga belang-belang atau campuran dari
warna-warna itu). Fitur semantis yang menyangkut warna pada kuda itu bisa
lebih dari satu, tetapi ada pula fitur semantis, seperti mata atau kaki yang
mutlak dalam arti fitur tersebut tidak terpisahkan dari makna kuda. Oleh
karena itu, kalimat (8a) berikut terasa lumrah, tetapi kalimat (8b) terasa aneh.
(8) a. Kuda saya ada belangnyz..
b. *Kuda saya ada matanyz.
Kalimat (8b) terasa aneh karena kalimat tersebut menyiratkan bahwa
ada kuda yang tidak mempunyai mata. Mata dan kaki merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari kuda.
Fitur semantis untuk kuda mencakupi pula berbagai kegiatan yang
dapat dilakukan oleh kuda, seperti berdiri, lari, dan makan. Akan tetapi,
ada juga kegiatan lain yang tidak biasa dilakukan oleh kuda, seperti duduk,
berbaring, dan bersiuL Pada contoh berikut tampak bahwa verba predikat
menuntut nomina subjek yang mempunyai fitur semantis tertentu.
(9) a. Kuda hitam itu sedang berlari.
b. *Kuda hitam itu sedang bersiul.
Kalimat (9a) berterima karena nomina subjek kuda memiliki fitur
semantis bernyawa dan berkaki yang merupakan syarat untuk dapat
melakukan perbuatan berlari. Akan tetapi, kalimat (9b) terasa aneh karena
fitur manusia yang merupakan syarat untuk dapat melakukan perbuatan
bersiul tidak ada pada kuda.
Pada tataran frasa, nomina atau frasa nominal dapat menjadi
pelengkap frasa preposisional. Makna frasa preposisional itu dapat berbedabeda bergantung pada fitur semantis nomina pelengkap preposisi itu.
(10) a. Baku itu ada di meja.
b. Buku itu ada di lad.
c. Buku itu ada di rumah.
Frasa di meja pada (10a) sama maknanya dengan di atas meja. Meja
adalah benda yang permukaannya merupakan bidang datar dan pada bidang
datar itu dapat digunakan sebagai tempat untuk meletakkan sesuatu. Frasa
di lad pada (10b) sama maknanya dengan di dalam lad. Lad merupakan
suatu benda yang berongga yang digunakan untuk menyimpan sesuatu di
dalamnya. Frasa di rumah pada (10c) sama maknanya dengan di dalam
rumah. Rumah merupakan benda yang mempunyai rongga atau ruang yang
relatif besar yang digunakan sebagai tempat tinggal orang. Frasa di rumah
pada (10c) dapat mempunyai makna lain jika subjeknya orang seperti pada
kalimat berikut.
(11) Ayah ada di rumah.
Frasa di rumah pada contoh (11) itu bermakna 'tinggal di rumah'.
Di sini fitur semantis rumah yang menentukan adalah fitur tempat tinggah
bukan fitur ruangan. Dari uraian pada (10) atas tampak bahwa fitur datar
pada meja serta rongga pada lad dan rumah menentukan apakah atas atau
dalam merupakan bentuk yang tepat yang dapat digunakan di antara
preposisi di dengan nomina pelengkapnya pada contoh (10). Karena rumah
juga mengandung fitur 'tempat tinggal' bagi orang, frasa di rumah dapat
mempunyai tafsiran lain kalau subjek kalimat berupa nomina yang memiliki
fitur semantis manusia seperti pada contoh (11). Karena bahasa berkembang
di dalam suatu budaya, kata-kata dalam suatu bahasa sering pula dipengaruhi
oleh budaya masyarakat yang bersangkutan. Fitur semantis kata-kata yang dipengaruhi budaya itu bersifat konvensional dan hanya muncul pada budaya
setempat. Misalnya, karena dalam tata budaya Indonesia peran lakl-laki lebih
dominan daripada perempuan, ada kegiatan yang menyangkut budaya yang
tidak biasa dilakukan oleh perempuan. Karena kendala semantis itu, kalimat
(12a) berikut (yang subjeknya nomina^^^w) tidak lumrah. Alih-alih kalimat
(12a), orang umumnya akan memakai kalimat (12b) atau (12c).
(12) a. Gadis itu akan menikahi Ahmad minggu depan.
b. Gadis itu akan nikah dengan Ahmad minggu depan.
c. Ahmad akan menikahi gadis itu minggu depan.
7.1.3 Nomina dari Segi Perilaku Sintaktisnya
Nomina atau frasa nominal dapat menduduki fungsi subjek (13a), objek
(13b), pelengkap (13c), keterangan atau adverbial (13d), dan predikat (13e)
pada tataran kalimat.
Contoh:
(13) a. Manusia ^zsx\ r[i2iX\.
Masalah penduduk memerlukan penanganan yang serius.
Pemerintahan Orde Baru berlangsung selama 32 tahun.
b. Perusahaan bus kota membutuhkan sopir.
Perusahaan itu sedang mencari manajeryang terampil.
Pemerintah Indonesia akan mengekspor beras.
c. Petani mulai enggan bertanam padi.
Itu baru merupakan suatu pendapat.
Ibunya meninggal sepuluh tahun lain.
d. Dia menyerupai ibunya.
Mereka akan tiba Minggu pagi.
Dia baru akan kembali bulan depan.
e. Andi murid terpandai di kelasnya.
Pak Hendri karyawan baru di kantor ini.
Ketua KONl sekarang mantan pemain tenis.
Nomina atau frasa nominal juga berfungsi sebagai pelengkap preposisi pada frasa preposisionai.
Contoh:
(14) di kantor — di persimpangan jalan
ke desa — ke negerijauh
dari markas — dari tempatpersembunyian
pada masa ini — pada hari ulang tahun
untuk adikmu — untuk kepentingan umum
Sebagai inti frasa, nomina merupakan unsur terpenting pada frasa
nominal. Unsur pemerluas, baik yang mendahului maupun yang mengikuti,
kehadirannya sangat bergantung pada nomina inti. Apabila pemerluas
mendahului nomina inti, unsur pemerluas itu umumnya berupa numeralia
dengan/atau tanpa penggolong atau partitif, seperti lima hari^ dua orang
mahasiswdy seekor anjing^ dua buah rumahy dan satu cangkir kopi. Kehadiran
atau ketidakhadiran penggolong orang, ekor, buah, dan partitif cangkir yang
mengikuti numeralia ditentukan oleh nomina inti. Nomina hari tidak dapat
didahului penggolong, nomina mahasiswa dapat didahului oleh orang, nomina
anjing oleh ekor, nomina rumah oleh buah, dan nomina kopi oleh cangkir.
7.1.4 Jenis Nomina
7.1.4.1 Nomina Berdasarkan Acuannya
Pada 7.1.1 telah dikemukakan bahwa nomina, berdasarkan jenis acuannya,
dapat dikelompokkan atas (1) nomina umum dan (2) nama diri. Nomina
berdasarkan acuannya juga dapat dibedakan atas nomina konkret (misalnya
buku, murid, dan air) dan nomina abstrak (misalnya kasih, masalah, dan
kesulitan). Di samping itu, nomina berdasarkan acuannya juga dapat
dibedakan atas nomina terbilang (misalnya guru, meja, dan masalah) dan
nomina takterbilang (misalnya rambut, hujan, dan hormat). Nomina
terbilang dapat diulang untuk menyatakan kejamakan (misalnya buku-buku,
mobil-mobil, dan kemudahan-kemudahan) atau didahului langsung oleh
bilangan untuk menyatakan jumlah (misalnya satu rumah, dua mahasiswa,
dan tiga masalah). Sebaliknya, nomina takterbilang tidak dapat diulang atau
didahului langsung oleh bilangan. Jadi, bentuk seperti hujan-hujan, rambutrambut, dua kesedihan, dan tiga hormat tidak lazim digunakan dalam bahasa
Indonesia untuk menyatakan makna jamak.
Nomina yang tergolong nomina umum, dapat berupa nama jenis,
memiliki acuan yang bersifat umum yang berubah-ubah dari waktu ke waktu
bergantung pada kapan, di mana, dan siapa yang memakainya. Kata pasar,
misalnya, tergolong nama jenis. Jika kalimat Ibu sedang ke pasar diucapkan
di Bandung oleh Santi dan kalimat yang sama diucapkan di Surabaya oleh
Lastri, tentu pasar yang dimaksud oleh Santi dan Lastri akan berbeda.
Dengan kata lain, acuan kata pasar pada ujaran Santi dan pada ujaran
Lastri berbeda. Sebaliknya, nomina yang tergolong nama diri memiliki acu
an spesifik yang unik dalam pandangan pembicara dengan pengertian acuannya relatif tetap. Kata Medan^ misalnya, tergolong nama diri. Kata
Medan pada kalimat Dia baru kembali dari Medan akan tetap mengacu pada
kota yang sama terlepas dari kapan, di mana, dan oleh siapa kalimat itu
diucapkan.
Nomina dalam bahasa Indonesia, khususnya yang tergolong
nama jenis yang acuannya tidak tentu, dapat didahului oleh numeralia dengan atau tanpa penggolong atau partitif, seperti {se)orangy {se)ekory {se)
batang, {se)buah^ {se)lembarlhelai, {se)potong, {se)gelas, 2X2Msuatu. Penggolong
yang digunakan sangat bergantung pada wujud dan jenis acuannya. Dalam
penurunan kata melalui afiksasi, pengulangan, atau pemajemukan dari bentuk
dasar nomina, umumnya hanya nama jenis yang dapat dipakai. Sebaliknya,
nomina yang tergolong nama diri tidak dapat didahului oleh numeralia de
ngan atau tanpa penggolong atau partitif. Nomina nama diri juga
tidak dapat menjadi pangkal untuk penurunan kata. Berikut ini disajikan contoh-contoh nomina berdasarkan jenis acuannya. Penggolongan kata berikut, walaupun tidak tuntas, dapat memberikan gambaran
mengenai nomina yang tergolong nama jenis dalam bahasa Indonesia.
7.1.4.1.1 Nama Jenis
Berdasarkan jenis acuannya, nomina yang tergolong nama jenis dapat
dibedakan sebagai berikut.
1) Nomina manusia, kata yang mengacu pada orang, dapat diberi penggolong
{se)orang.
Contoh:
(15) adik
guru
hakim
dokter
polisi
2) Nomina binatang, kata yang mengacu pada binatang, dapat diberi
penggolong {se)ekor.
Contoh;
(16) ayam
ikan
kucing
ular
belalang
3) Nomina tumbuhan, kata yang mengacu pada berbagai tumbuhan, baik
yang berbatang maupun yang tidak berbatang, lazim diberi penggolong
{se)batang.
Contoh:
(17) bambu
rotan
kayu
pad!
tebu
4) Nomina benda, yaitu kata yang mengacu pada benda/fenomena alam,
benda budaya, atau benda angkasa. Nomina yang tergolong kelompok
ini dapat diberi penggolong {se)buah jika bentuknya relatif tetap.
Kata-kata yang tidak dapat diberi penggolong {se)buah dapat diberi
penggolong atau partitif lain, seperti {se)bidang {tanah)y {se)gelas {air),
atau {se)karung {pasir).
Contoh:
(18) bintang
candi
halilincar
gunung
meja
5) Nomina temporal, yaitu kata yang mengacu pada waktu. Nomina
kelompok ini dapat didahului numeraiia. Anggota kelompok nomina
temporal ini relatif terbatas.
Contoh:
(19) hari
minggu
bulan
tahun
abad
windu
malam
jam
menit
6) Nomina numeraiia, yaitu kata yang menyatakan satuan bilangan.
Nomina numeraiia dalam bahasa Indonesia terbatas. Berikut diberikan
daftar nomina numeraiia yang ada dalam bahasa Indonesia.
Contoh:
(20) puluh
belas
ratus
laksa
ribu
juta
miliar
triliun
7) Nomina ukuran, yaitu kata yang menyatakan satuan ukuran panjang, isi,
berat, jarak, atau kuantitas. Anggota nomina ukuran ini terbatas. Kata
yang tergolong nomina ukuran biasanya didahului oleh kata bilangan.
Berikut diberikan daftar nomina ukuran yang terdapat dalam bahasa
Indonesia
Contoh:
(21) bare!
gantang
gram
kaki
kaci
knot
kodi
liter
lusin
meter
mil
Di samping kata-kata di atas dalam bahasa Indonesia dikenal juga satuan
ukuran lain yang sifatnya relatif karena tidak ditera, sc^cxxX jengkal, hasta,
depa, dan langkah.
8) Nomina konsep adalah kata yang menyatakan konsep atau pengertian.
Umumnya nomina yang tergolong dalam kelompok ini tidak dapat
didahului penggolong.
Contoh:
(22) atas
bawah
luas
panjang
cinta
kasih
hormat
kesedihan
masalah
9) Nomina lokatif, yaitu kata yang mengacu pada benda yang menyatakan
tempat.
Contoh:
(23) kota
kampung
jalan
pelabuhan
rumah
7.1.4.1.2 Nama Diri
Nomina yang tergolong nama diri digunakan untuk mengacu, antara lain,
pada orang, dewa, tempat, gejala geografi, waktu, benda angkasa, atau badan
tertentu. Pada dasarnya nama diri tidak dapat didahului numeralia atau
penggolong. Nama diri dapat terdiri atas satu kata dan dapat pula terdiri atas
dua kata atau lebih. Perlu diingat bahwa huruf awai tiap kata nama diri ditulis
dengan huruf kapital. Berikut disajikan contoh nama diri berdasarkan jenis acuannya.
1) Nama diri orang adalah kata yang digunakan untuk mengacu atau
mengidentifikasi orang tertentu.
Contoh:
(24) Agus
Basri
Indri
Tri
Elvi
2) Nama diri lokatif adalah kata yang mengacu pada tempat ter
tentu.
Contoh:
(25) Bandung
London
Makassar
Merauke
Tokyo
3) Nama diri geografi adalah kata yang mengacu pada fenomena geografi
tertentu, seperti benua, pulau, laut(an), danau, sungai, dan gunung.
Contoh:
(26) Asia
(Laut) Jawa
Papua
(Gunung) Merapi
(Sungai) Musi
Kata-kata nama jenis, seperti laut, selat, sungai, kali, danau, dan gunung
pada contoh di atas ditulis dengan huruf kapital karena diperlakukan
sebagai bagian dan nama din.
4) Nama diri temporal adalah kata yang mengacu pada waktu atau hari
penting tertentu.
Contoh:
(27) Senin
Februari
Idulfitri
Natal
Galungan
Saka
5) Nama diri bangsa, negara, atau bahasa adalah kata yang mengacu pada
bangsa, ras, etnis, negara atau bahasa tertentu. Kata-kata yang menjadi
nama diri ini umumnya didahului kata-kata, seperti bangsa, suku, orang,
negara, negeri, atau bahasa.
Contoh:
(28) (bangsa) Indonesia
(negeri) Mesir
(negara) Jepang
(bahasa) Inggris
(suku) Jawa
(orang) Sumatra
6) Nama diri keagamaan adalah kata yang mengacu pada agama atau kitab
suci agama tertentu.
Contoh:
(29) Islam
Buddha
Hindu
Kristen
Alquran
7) Nama diri benda langit adalah kata yang mengacu pada bintang atau
planet.
Contoh:
(30) Pluto
Yupiter
Neptunus
Saturnus
Venus
8) Nama diri Tuhan atau dewa adalah kata yang mengacu pada pribadi Tuhan atau dewa tertentu.
Contoh:
(31) Allah
Brahma
Syiwa
Wisnu
Zeus
9) Nama diri lembaga adalah kata yang mengacu pada lembaga, badan, atau
fasilitas umum tertentu.
Contoh:
(32) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Garuda Indonesia Airways (CIA)
Hotel Indonesia
10) Nama diri peristiwa atau dokumen pen ting adalah kata-kata yang
mengacu pada peristiwa atau dokumen penting.
Contoh:
(33) Hari Proklamasi Kemerdekaan
Hari Sumpah Pemuda
Kongres Bahasa Indonesia
Undang-Undang Dasar 1945
Magna Charta
Perang Dunia II
ll)Nama diri terbitan adalah kata-kata yang mengacu pada judul buku,
majalah, jurnal, koran, atau artikel.
Contoh:
(34) Republika
Tempo
Salah Asuhan
Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia
Metalingua
Widya Parwa
7.1.4.2 Nomina berdasarkan Bentuk Morfologisnya
Jika dilihat dari segi bentuk morfologisnya, nomina dapat dikelompokkan atas dua macam, yakni (1) nomina dasar dan (2) nomina turunan.
Penurunan nomina yang lazim dalam bahasa Indonesia dilakukan dengan (a)
konversi, (b) afiksasi, (c) pengulangan, dan (d) pemajemukan. Secara skematis,
nomina bahasa Indonesia, berdasarkan bentuk dan cara pembentukannya,
dapat digambarkan sebagai berikut.
7.1.4.2.1 Nomina Dasar
Nomina dasar adalah nomina yang terdiri atas satu morfem. Jika dilihat dari
segi pembentukan kata, nomina dasar dapat dikelompokkan atas (a) nomina
dasar umum dan (b) nomina dasar khusus.
1) Nomina Dasar Umum
Nomina dasar umum adalah nomina yang dapat menjadi dasar untuk penurunan kata atau leksem baru. Nomina yang termasuk dalam kelompok ini
pada umumnya adalah nomina yang tergolong nama jenis.
Contoh:
(35) orang orang-orangan, perseorangan
meja meja makan, meja tulis
rumah -> rumah-rumahan, perumahan
malam bermalam, kemalaman
gambar gambarkan, gambaran
minggu mingguan, berminggu-minggu
pisau pisau dapur, pisau lipat
tongkat bertongkat, tongkat komando
cinta -> bercinta, mencintai
bawah bawahan, membawahi
2) Nomina Dasar Khusus
Nomina dasar khusus adalah nomina yang relatif tidak dapat men
jadi dasar penurunan kata atau leksem baru. Termasuk dalam kelompok ini
adalah nomina dasar yang tergolong nama diri {Ana, Dani, Indonesia) dan
pronomina {saya, kamu, did). Perlu diingat bahwa di antara kata-kata yang
tergolong nama diri, ada juga yang dapat dijadikan dasar penurunan leksem
baru, yaitu nama diri yang mengacu pada bangsa atau bahasa.
Contoh:
(36) a. Mereka bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia.
b. Mereka berusaha mengindonesiakan istilah-istilah asing.
(37) a. Pak Anwar banyak bergaul dengan orang-orang Belanda.
b. Karena pergaulannya, Pak Anwar menjadi kebelandabelandaan.
Dari nama diri Indonesia dan Belanda verba mengindonesiakan dan
adjektiva kebelanda-belandaan dapat diturunkan.
7.1.4.2.2 Nomina Turiman
Nomina dapat diturunkan melalui konversi (derivasi nol), pengafiksan, pengulangan, atau pemajemukan. Konversi nomina adalah penurunan nomina dari kelas kata lain tanpa menambahkan afiks atau mengubah
bentuknya, misalnya dalam (nomina<adjektiva), tinggi (nomina<adjektiva),
dan harian (nomina<adjektiva). Pengafiksan nomina adalah pembentukan
nomina dengan menambahkan afiks atau imbuhan tertentu pada bentuk
pangkal, misalnya tulisan {<tulis+an), pendiam {<peng-\rdiam), dan kesedihan
{<sedih-\-ke-...-an). Pengulangan nomina adalah penurunan nomina dengan
jalan mengulang bentuk pangkal, misalnya kuda-kuda {<kuda + Red), orangorangan {<{orang + Red) + an), dan tetangga {<{tangga + Red) + salin suara).
Pemajemukan nomina adalah pembentukan leksem baru berupa nomina
dengan jalan menggabungkan dua kata, misalnya rumah sakit, matahari,
saputangan, dan kereta api. Bentuk matahari dan saputangan disebut nomina
majemuk kata karena diperlakukan sebagai kata, sedangkan bentuk rumah
sakit dan kereta api disebut majemuk frasa karena diperlakukan sebagai frasa.
Bentuk pangkal itu dapat berupa pangkal (monomorfemis) dan
dapat pula berupa kata turunan (polimorfemis). Nomina turunan,
seperti kebesaran memang diturunkan dari pangkal besar (adjektiva),
tetapi pembesaran tidak diturunkan dari pangkal yang sama, melainkan dari membesarkan (verba). Bentuk yang menjadi pangkal penurunan
nomina ditentukan oleh keterkaitan makna antara bentuk pangkal dan
turunannya, seperti yang terlihat pada bagan berikut.
Karena keterkaitan makna merupakan dasar untuk menentukan
bentuk pangkal penurunan, dalam kebanyakan hal nomina turunan
mempunyai bentuk pangkal sendiri-sendiri. Nomina temuan, pertemuan^
dan penemuan, misalnya, masing-masing diturunkan dari bentuk pangkal
yang berbeda, yakni temu, bertemu, dan menemukan.
Dalam bahasa Indonesia sering ada dua verba yang maknanya
sangat dekat. Verba membesarkan dan memperbesar, misalnya, sama-sama
mengandung makna 'menyebabkan sesuatu menjadi besar atau lebih besar'.
Karena kedekatan makna verba itu, bentuk pangkal nomina pembesaran bisa
membesarkan dan bisa juga memperbesar.
1) Penurunan Nomina dengan Konversi
Dalam bahasa Indonesia terdapat sejumlah nomina konversi, yaitu nomina
yang diturunkan dari kelas kata lain tanpa menambahkan afiks atau mengubah
bentuk pangkalnya. Bentuk pangkal nomina konversi dalam bahasa Indonesia
umumnya tergolong adjektiva. Kata tinggi, panjang, dan dalam pada (38)
berikut tergolong adjektiva, sedangkan pada (39) tergolong nomina.
(38) a. Tugu itu ting^i sekali.
b. Perjalanan kita masih panjang.
c. Sungai itu cukup daUim untuk dilayari kapal besar.
(39) a. Tinggi tugu itu lebih dari seratus meter.
b. Panjang jembatan itu lebih dari dua ratus meter.
c. Dalam sungai itu lebih dari tiga puluh meter.
Bahwa nomina tinggi^ panjang^ dan daLtm merupakan bentuk
turunan melalui konversi dari adjektiva, bukan sebaliknya yang didasarkan
pada pertimbangan bahwa keadjektivaan kata-kata itu lebih dominan secara
intuitif. Di samping itu, sebagian besar adjektiva jenis itu dapat menjadi
pangkal penurunan nomina dengan ke'...-an, seperti pada ketinggian dan
kedalaman.
Nomina konversi dalam bahasa Indonesia dapat berasal dari adjektiva
dasar atau adjektiva turunan dan dapat pula dari verba. Berikut diberikan
contoh nomina turunan melalui konversi berdasarkan jenis dasarnya.
1) Nomina turunan dari adjektiva yang menyatakan ukuran atau sukatan.
Contoh:
(40) dalam
tinggi
lebar
panjang
luas
berat
2) Nomina turunan dari adjektiva (turunan) yang menyatakan terbitan atau peristiwa yang dilakukan secara berkala,
Contoh:
(41) harian
bulanan
mingguan
tahunan
3) Nomina turunan dari verba yang menyatakan orang yang mengalami' hal yang dinyatakan bentuk pangkal.
Contoh:
(42) terdakwa
terpidana
termohon
tergugat
tersangka
terhukum
tertuduh
2) Penuriman Nomina melalui Pengafiksan
Pada dasarnya ada tiga prefiks dan satu sufiks yang dipakai untuk menandai
nomina, yaitu prefiks ke-, per-^ dan peng- serta sufiks -an. Di samping itu,
terdapat tiga gabungan afiks (konfiks) sehingga seluruhnya ada tujuh macam
afiksasi dalam penurunan nomina. Di antara afiks dan gabungan afiks itu
ada yang sama bentuknya (berhomonim) dengan afiks yang dipakai untuk
penurunan kelas kata lain. Subskrip pada daftar berikut menunjukkan
bahwa afiks atau gabungan afiks itu berhomonim dengan afiks pembentuk
kelas kata lain.
ke- ( ^ir
)
-an ()
ke-...-an ( )
per- („)
peng-...-an
pengper-...-an
Dalam pembicaraan selanjutnya subskrip itu ditiadakan kecuali jika
akan menyebabkan salah tafsir.
Prefiks per- mempunyai tiga alomorf, yakni per-., pel-, dan pe-.
Prefiks peng- mempunyai enam alomorf, yaitu pern-, pen-, peny-, pe-, peng-
, dan penge-. Karena prefiks per- ataupun peng- mempunyai alomorf yang
wujudnya sama, yakni pe- dan kedua prefiks tersebut dapat mempunyai fungsi
yang sama, yaitu sebagai pembentuk nomina pelaku, dalam menentukan
keanggotaan pe- ini perlu diperhatikan bentuk verba yang menjadi pangkal
nomina dengan pe- itu. Jika nomina itu berkaitan dengan verba berawalan
meng-, pe- pembentuk nomina tersebut merupakan alomorf dari peng-. Jika
berkaitan dengan verba yang berawalan ber-, pe- pembentuk nomina itu adalah alomorf dari per-. Nomina berikut diturunkan dengan memakai dua
prefiks yang berbeda meskipun wujudnya sama.
Contoh:
(43) pev^^ns
/>dukis
/>^masak
< mewariskan
< meiukis
< memasak
< mewariskan
< meiukis
(<memasak)
pe- adalah
^ alomorf
dari peng-
(44) /Jf-dagang < berdagang
pet^inx < bertani
pex\n]yx < bertinju
^ pe- adalah alomorf dari perKelompok (43) diturunkan dengan menggunakan prefiks pengyang mengalami proses morfofonemik (proses asimilasi) yang teratur, yaitu
peng- menjadi pe- apabila ditambahkan pada kata yang berawal dengan
konsonan sonoran, yaitu nasal /m, n, g/, lateral /I/, tril /r/, atau semivokal
/w, y/. Kelompok (44) diturunkan dengan menggunakan prefiks per- yang
mengalami proses morfofonemik yang tidak teratur. Bentuk pedagang,
misalnya, diturunkan dari verba berdagang yzng mengandung konsonan /r/.
Di samping prefiks dan sufiks di atas, ada pula infiks meskipun
kini tidak produktif lagi. Infiks-infiks itu adalah -el-, -em-, -er-, dan
-in-. Karena adanya kontak dengan bahasa lain, kini bahasa
Indonesia juga memiliki afiks yang berasal dari bahasa asing: -wan,
-wati, -at, -in, -isme, -{is)asi, -logi, dan -tas. Bahasa Indonesia, seperti halnya
dengan bahasa yang hidup pada umumnya, memanfaatkan pengafiksan
untuk memperkaya kosakatanya. Penurunan nomina melalui afiksasi
dilakukan dengan memakai tiga prefiks: ke-, peng- (beserta alomorfnya), dan
per- (beserta alomorfnya); satu sufiks {-an)-, tiga konfiks berupa gabungan
antara prefiks dan sufiks ke-...-an, peng-...-an (beserta alomorfnya), sertaper-
...-an (beserta alomorfnya).
1) Penurunan Nomina dengan keNomina yang diturunkan dengan penambahan prefiks ke- dalam bahasa
Indonesia terbatas pada kata-kata berikut.
ketua
kehendak
kekasih
kerangka
Proses ini tidak produktif lagi, tetapi menarik untuk diingat bahwa banyak nama tumbuhan dan binatang yang dimulai dengan ke-y
misalnya kelapa, kenarU kemirU kepiting, kelinch dan kelelawar.
2) Penurunan Nomina dengan perPrefiks per- mempunyai tiga alomorf, yaitu pel-, per-, dan pe-. Distribusi
pel- dan per- sejajar dengan distribusi bel- dan ber-. Maksudnya, kata yang
dapat diberi pel- terbatas pada pangkal yang dapat diimbuhi bel--, kata
yang dapat diberi per- terbatas pada pangkal yang dapat diimbuhi ber-.
Distribusi pe- dapat dikelompokkan atas tiga: (1) pe- yang ditambahkan
pada pangkal yang dapat diberi be- yang tunduk pada kaidah fonologi,
(2J pe- yang ditambahkan pada pangkal yang dapat diberi ber-, tetapi
karena perkembangan sejarah, konsonan <r> (/r/) hilang, dan (3) /J^-'yang
ditambahkan pada pangkal yang tidak bertalian dengan verba dengan
ber-.
Dalam bahasa Indonesia hanya ada satu pangkal, yakni ajar,
yang dapat diberi pel- untuk menurunkan nomina pelajar. Bentuk
ini berkaitan dengan verba belajar. Nomina yang diturunkan dengan
alomorf per- dalam bahasa Indonesia dewasa ini tidak banyak.
Meskipun banyak verba berafiks ber- yang berkaitan dengan penurunan nomina dengan per-, dalam pertumbuhannya banyak no
mina dengan per- yang tidak lagi mempertahankan konsonan /r/-nya
sehingga nomina tersebut muncul hanya dengan pe- saja. Yang masih
mempertahankan bentuk per- sangat terbatas.
perlambang <— berlambang
persegi <— bersegi
pertanda <— bertanda
pertapa <— bertapa
Nomina turunan lain muncui dengan pe- walaupun berkaitan dengan verba ber-.
Contoh:
(45) pedagang
pejaian (kaki)
pejuang
petani
pemain
penyanyi
petinju
berdagang
berjalan (kaki)
berjuang
bertani
bermain
bernyanyi
bertinju
Bahwa pe- pada contoh-contoh di atas berasal dari aiomorf perdapat pula dilihat dari bentuk nomina lain yang juga berkaitan dengan
verba ber- dan masih mempertahankan bentuk per-.
Contoh:
(46) pedagang
pejaian
pejuang
pemain
petani
petinju
perdagangan
perjalanan
perjuangan
permainan
pertanian
pertinjuan
berdagang
berjalan
berjuang
bermain
bertani
bertinju
Selain pe- yang berkaitan dengan verba dengan ber-^ ada nomina
turunan dengan pe- yang tidak berkaitan langsung dengan verba dengan ber-.
Penurunan nomina dengan pe- jenis ini didasarkan pada analogi. Fungsi
pe- di sini adalah membentuk nomina pelaku atau pengalam profesi yang
dinyatakan oleh pangkal.
Contoh:
(47) pebasket
pebulu tangkis
pegolf
perenang
pehoki
pesinetron
petenis
peselancar
pesepak bola
petata
Penurunan nomina dengan alomorf pe- yang tunduk pada kaidah fonologis terbatas pada pangkal yang berawalan be-. Namun, tidak
semua verba dengan be- dapat menjadi pangkal pembentukan nomina
dengan pe-. Ini terutama karena kendala semantis. Jadi, walaupun
ada verba becermin, berapat, dan berumah tidak ada nomina turunan
*pecerminy *perapat, atau *perumah. Perbuatan yang dinyatakan oieh
verba be{r)cermin, berapat, dan berumah tidak mengandung fitur profesi.
Berikut adalah nomina turunan dengan pe- yang berkaitan dengan verba
berawalan be-.
pekerja •<— bekerja
perenang <— berenang
peternak <— beternak
peserta •<— beserta
pesolek bersolek
3) Penurunan Nomina dengan pengPrefiks peng- sangat produktif dalam bahasa Indonesia. Prefiks pengmempunyai enam alomorf, yaitu pem-y pen-y peny-y pe-y penge-y dan
peng- yang distribusinya paralel dengan distribusi alomorf prefiks verba
mem-y men-y meny-y me-y menge-y dan meng-. Pada dasarnya, pemakaian
alomorf-alomorf itu tunduk pada kaidah fonologi. Alomorf pern- dipakai
apabila pangkalnya berawal dengan konsonan obstruen labial (/p, b,
f/), pen- apabila pangkalnya berawal dengan konsonan hambat alveolar
(/t, d/), peny- (/p9ji/) apabila pangkalnya berawal dengan konsonan
alveolar frikatif atau palatal hambat (/s, c, j/), pe- apabila pangkalnya
berawal dengan konsonan sonoran (/m, n, ji, g, 1, r, w, yi)ypenge- apabila
pangkalnya bersuku satu, dan peng- apabila pangkalnya berawal dengan
vokal atau konsonan yang lainnya. Jika pangkalnya hanya bersuku
satu, penurunan nomina dengan prefiks peng- dapat dilakukan dengan
dua cara. Pertama, dengan menggunakan alomorf yang sesuai dengan
bunyi awal pangkal. Cara pertama ini dapat dirumuskan sebagai peng- +
asimilasi + bentuk dasar. Kedua, dengan menambahkan alomorf pengepada kata dasar. Jadi, dari kata bom dapat diturunkan nomina pembom
{<pem + bom {<peng- + asimilasi + bom)) ataupengebom {<peng- + sisipan
-e-{hl) + bom). Untuk memudahkan pengenalan bentuk dasar, kaidah
penyisipan <e> (penggunaan alomorfpenge-) wajib ditetapkan pada katakata pangkal yang berawal dengan pangkal konsonan /p, t, k/ dan /si.
Pada umumnya nomina dengan peng- dibentuk dengan menyubstitusi
alomorf meng- dengan alomorf peng- yang sejajar lalu menanggalkan
sufiks pangkal kalau ada.
a) Nomina dengan peng- yang diturunkan dari verba umumnya ^^-rmakna
pelaku perbuatan yang dinyatakan verba. Nomina dengan peng- yang
diturunkan dari verba umumnya bermakna pelaku perbuatan yang
dinyatakan verba.
Contoh:
(48) penulis 'orang yang menulis'
pembaca 'orang yang membaca'
pembantu 'orang yang membantu'
pemilih 'orang yang memilih'
pencuri 'orang yang mencuri'
pendatang 'orang yang datang'
pendengar 'orang yang mendengaf
penulis 'orang yang menulis'
penyerang 'orang atau binatang yang menyerang'
perusak 'orang atau binatang yang merusak'
b) Nomina dengan peng- yang diturunkan dari verba dengan mengdapat menyatakan makna orang yang pekerjaannya melakukan
kegiatan yang dinyatakan oleh verba. Makna ini berkaitan erat
dengan makna verba yang menjadi pangkal penurunan dengan
peng-. Apabila makna verba pangkal itu memungkinkan terciptanya suatu profesi, makna profesi inilah yang lebih dominan
dalam penafsiran makna nomina turunan itu. Kara pelatih^ misalnya, cenderung ditafsirkan sebagai seseorang yang pekerjaannya
melatih. Seseorang yang pada suatu saat melatih anaknya bermain bulu tangkis, misalnya, umumnya tidak disebut sebagai
pelatih meskipun tafsiran itu dapat diberikan bagi bentuk itu.
Sebaliknya, pendobrak lazimnya tidak akan ditafsirkan sebagai
seseorang yang pekerjaannya mendobrak karena verba mendobrak menyatakan perbuatan yang dilakukan satu kali. Nomina
turunan jenis ini relatif banyak.
Perlu diingat di sini bahwa tidak semua nomina dengan
peng- memiliki salah satu arti yang disebutkan di atas. Kata penyakiu
misalnya, yang semula mungkin berarti yang menyakiti' sudah meluas
artinya dan mencakupi makna 'gangguan pada bagian tubuh, gangguan
kesehatan, atau kebiasaan yang buruk', dan sesuatu yang mendatangkan
keburukan'. Sebaliknya, kata pembesar tidak merujuk pada sifat fisik
seseorang yang besar, tetapi telah dipakai secara metaforis untuk merujuk
kepada seseorang yang kedudukan atau jabatannya tinggi atau penting.
Demikian pula halnya dengan makna pelaku pada peng-. Walaupun
peng- produktif, tidak semua makna pelaku dinyatakan dengan peng-.
Orang yang membeli barang dagangan untuk dijual kembali tidak disebut
*pengulak, tetapi tengkulak. Orang yang pekerjaannya mengajar murid
lebih lazim disebut guru alih-alih pengajar. Kenyataan bahwa pe- yang
merupakan alomorf peng- dan juga alomorf per- seperti disebutkan pada
7.1.4.2 menyebabkan orang perlu mengetahui hubungan antara nomina
dengan pe- dan verba pangkal nomina tersebut.
Contoh:
(52) pedagang — (orang yang) ^^rdagang alomorf dari perpelatih — (orang yang) wdatih alomorf dari pengperawat — (orang yang) w<?rawat ■«-> alomorf dari pengpetani — (orang yang) ^mani alomorf dari perpetinju — (orang yang) ^minju alomorf dari perpewatas — (sesuatu yang) wcwatasi ^ alomorf dari pengPerkembangan bahasa Indonesia selanjutnya memunculkan
pula bentuk-bentuk baru yang di satu pihak didasarkan analogi dengan
bentuk yang sudah ada sebelumnya, tetapi di pihak lain juga ditopang
oleh perkembangan pada aspek lain terutama verba. Bentuk yang semula
terbatas dan tidak memiliki kontras makna kemudian berkembang
sehingga kini terdapat bentuk-bentuk kontras antara nomina pelaku
(agentif) dan nomina pengalam (sasaran) seperti berikut.
(53) penyuruh — yang menyuruh
pesuruh — yang disuruh
peninju — yang meninju
petinju — yang bertinju
penyerta — yang menyertai
peserta — yang ikut serta
penatar — yang menatar
petatar — yang ditatar
penyuluh — yang menyuluh
pesuluh — yang disuluh
Makna 'pelaku', baik dalam bentuk peng- maupun dalam bentuk
per-y begitu produktif sehingga dipakailah sebagai analogi untuk
menciptakan bentuk-bentuk baru, seperti pemakalahy pegolfy pecatuvy
peselancar, dan petenis. Perkembangan baru ini menarik untuk disimak
karena pada umumnya nomina yang bermakna orang yang' memiliki
verba atau adjektiva sebagai dasarnya. Namun, dalam contoh-contoh di
atas tidak ada verba atau adjektiva yang bertalian dengan makalahy golfy
catuvy selancavy dan tents kecuali jika dikaitkan dengan verba menulis atau
bermain: menulis makalahy bermain golfy bermain catur, bermain selancaVy
dan bermain tenis.
4) Penurunan Nomina dengan —an
Nomina dengan sufiks -an umumnya diturunkan dari bentuk pangkal
verba walaupun kata dasarnya adalah kelas kata yang lain. Kara asiny
misalnya, termasuk adjektiva, tetapi kata itu dijadikan verba asinkan
atau asini terlebih dahulu sebelum dipakai sebagai bentuk pangkal untuk
menurunkan nomina asinan. Demikian pula halnya dengan nomina kiloan.
Bentuk kiloan diturunkan bukan langsung dari nomina kiloy melainkan
dari verba mengilo-{kan).
Nomina dengan -an dapat diturunkan dari bentuk pangkal
verba dan dari bentuk pangkal nomina. Makna nomina dengan
-an itu bergantung pada makna bentuk pangkalnya. Berikut diberikan
contoh-contoh nomina dengan -an berdasarkan maknanya.
a) Nomina dengan -an yang diturunkan dari verba yang menyatakan
perbuatan umumnya mempunyai makna 'basil perbuatan atau sesuatu
yang dinyatakan oleh verba pangkal'.
Contoh:
(54) anjuran — hasil menganjurkan atau sesuatu yang
dianjurkan
asinan
guntingan -
kiloan
kiriman
tulisan
- hasil mengasinkan atau sesuatu yang
diasinkan
- hasil menggunting atau sesuatu yang
digunting
- hasil mengilo atau sesuatu yang dikilo
-- hasil mengirim atau sesuatu yang dikirimkan
- hasil menulis atau sesuatu yang ditulis
b) Nomina dengan —an yang diturunkan dari verba keadaan atau no
mina dapat juga menyatakan makna 'lokasi'.
Contoh:
(55) akhiran — yang ditempatkan di akhir
awalan — yang ditempatkan di awal
belokan — tempat membelok
tanjakan — tempat yang menanjak
tepian — tempat menepi atau bagian yang di tepi
turunan — tempat yang menurun
Dalam kelompok ini dapat ditambahkan nomina daratan dan lautan
yang masing-masing bermakna 'bagian permukaan bumi berupa
darat yang luas' dan 'bagian permukaan bumi berupa laut yang luas'.
c) Nomina dengan -an yang diturunkan dari nomina numeralia me
nyatakan bilangan kelipatan numeralia dasar.
Contoh:
(56) satuan — bilangan yang menyatakan kelipatan satu
— bilangan yang menyatakan kelipatan sepuluh
— bilangan yang menyatakan kelipatan seratus
— bilangan yang menyatakan kelipatan seribu
— bilangan yang menyatakan kelipatan sejuta
d) Nomina dengan -an dapat diturunkan dari verba untuk menyatakan
makna 'kumpulan orang, hewan, atau alat untuk melakukan yang
dinyatakan verba'.
Contoh:
(57) kawanan — sejumlah orang atau hewan yang
berkawan
pasukan — sejumlah orang atau binatang yang
berpasuk-pasuk
gerombolan — sejumlah orang atau binatang yang
bergerombol
pimpinan — sejumlah orang yang memimpin secara
bersamaan
mainan — alat yang dijadikan untuk bermain
Dalam pemakaian dewasa ini, gerombolan cenderung digunakan
untuk mengacu pada kelompok orang yang mengacau atau berbuat
keonaran.
5) Penurunan Nomina dengan peng-... -an
Nomina dengan peng-...-an umumnya diturunkan dari verba dengan
meng- yang berstatus transitif. Apabila ada dua verba dengan pangkal yang sama dan salah satu verba itu berstatus transitif, sedangkan
yang lainnya taktransitif, verba transitiflah yang menjadi dasar pe
nurunan nomina dengan peng-...-an. Misalnya, dalam bahasa Indo
nesia terdapat verba bersatu dan menyatukan. Nomina penyatuan tidak
diturunkan dari verba taktransitif bersatUy tetapi dari verba transitif
menyatukan. Simpulan ini didasarkan pada (1) adanya keterkaitan
makna antara penyatuan dan menyatukan^ yakni bahwa penyatuan adalah
'perbuatan menyatukan' dan (2) adanya keselarasan sintaktis antara verba
menyatukan dan nomina penyatuan seperti contoh berikut.
(58) a. Hayam Wuruk menyatukan seluruh Nusantara.
b. Penyatuan seluruh Nusantara dilakukan oleh Hayam Wuruk.
(59) a, Seluruh Nusantara bersatu.
b. *Persatuan seluruh Nusantara dilakukan oleh Hayam Wuruk.
Kalimat (58a) dan (59b) pada dasarnya menyatakan proposisi
atau makna yang sama. Pada kedua kalimat itu Hayam Wuruk merupakan pelaku (agen) perbuatan yang terkandung pada verba menyatukan
dan nomina penyatuan. Dengan cara lain dapat dikatakan bahwa nomina
penyatuan merupakan 'perbuatan menyatukan'. Ketidakberterimaan
kalimat (59b) mendukung simpulan bahwa nomina peng-...'an diturunkan dari verba transitif.
Penurunan nomina dengan peng-...-an sangat produktif. Oleh
karena itu, tiap kali ada verba transitif cenderung akan dapat diturunkan nomina dengan peng-... -an. Acap kali muncul nomina dengan
peng-...-an yang belum lazim dipakai, tetapi para penutur asli dapat
menerka dengan tepat apa makna bentuk itu. Misalnya, dalam bahasa
Indonesia terdapat adjektiva hitam dan verba menghitamkan. Atas
dasar keproduktifan penurunan nomina dengan peng-...-an itu, dapat
dibentuk nomina penghitaman. Jika dibandingkan dengan pemutihan
dan penghijauan., bentuk penghitaman (dan banyak lagi nomina lain,
seperti pemerahan, pembiruan, pengunguan) belum lazim dipakai, tetapi
para penutur asli tahu makna kata-kata yang potensial ada dalam bahasa
Indonesia.
Seperti halnya dengan nomina dengan peng-., nomina dengan
peng-...-an juga mempunyai enam alomorf: pem-...-an., pen-...-an,
peny-... -an, pe-... -an, penge-... -an, dan peng-... -an. Distribusi alomorfalomorf konfiks peng-...-an ini sejajar dengan distribusi alomorfalomorf afiks peng-. Konfiks peng-...-an lazimnya digunakan untuk
membentuk nomina dengan menyubstitusi prefiks meng- dengan
peng- lalu menambahkan sufiks -an pada pangkal setelah semua
sufiks verba ditanggalkan. Konfiks peng-...-an dapat ditambahkan
pada verba dengan meng- yang dasarnya monomorfemis atau polimorfemis (berafiks atau majemuk) untuk menyatakan makna 'per
buatan, proses, atau hal/hasil yang dinyatakan verba pangkal'.
Contoh:
(60) a. Pembangunan jembatan itu dilakukan oleh kontraktor Jepang.
b. Perbuatan membangun jembatan itu dilakukan oleh
kontraktor Jepang.
(61) a. Pembangunan jembatan itu berlangsung selama dua tahun,
b. Proses membangun jembatan itu berlangsung selama dua tahun.
(62) a. Pembangunan jembatan itu memperlancar lalu lintas barang.
b. Hasil membangun jembatan itu memperlancar lalu lintas
barang.
(63) a. Pengakuannya di depan guru dilakukannya karena terpaksa.
b. Perbuatannya mengaku di depan guru dilakukannya karena
terpaksa.
(64) a. Pengakuannya di depan polisi disangkalnya di pengadilan.
b. Halyang diakuinya di depan polisi disangkalnya di pengadilan.
(65) * Pengakuannya di depan polisi dilakukannya selama satu jam.
Tafsiran konfikspeng-...-an sebagai perbuatan, proses, atau cara
perbuatan yang dinyatakan verba sangat bergantung pada jenis verba
dasar dan konteks pemakaiannya. Keberterimaan kalimat (60—64)
menunjukkan bahwa nomina pembangunan dapat bermakna 'perbuatan,
proses, atau cara membangun'. Sementara itu, keberterimaan kalimat
(63—64) dan ketidakberterimaan kalimat (65) menunjukkan bahwa
nomina pengakuan hanya dapat menyatakan makna 'perbuatan' atau
'hasil/hal yang diakui'.
Berikut adalah contoh-contoh nomina turunan dengan peng-,..
-an yang menggambarkan ketiga makna tersebut.
a) Nomina dengan peng-... -an umumnya menyatakan perbuatan.
Contoh:
(66) pemberdayaan 'perbuatan memberdayakan'
pemberhentian 'perbuatan memberhentikan'
pemukulan 'perbuatan memukul'
pengampunan 'perbuatan mengampuni'
penindakan 'perbuatan menindak'
b) Nomina dengan peng-...-an dapat menyatakan makna proses di
samping makna perbuatan. Makna proses muncul jika verba dasarnya
mengandung aspek duratif.
Contoh:
(67) pembelajaran
pembicaraan
pengurusan
pengadilan
penulisan
proses membelajarkan'
proses membicarakan'
proses mengurus'
proses mengadili'
proses menulis'
c) Nomina dengan peng-.-.-an dapat juga menyatakan makna hasil/
hal yang dinyatakan verba di samping makna perbuatan atau proses.
Makna hasil/hal tersebut dapat muncul jika verba pangkalnya
mengandung fitur rampungan {accomplishment).
Contoh:
(68) pemberitahuan 'hasil/hal memberitahukan'
Perlu ditambahkan di sini bahwa ada juga nomina peng-.-.-an
yang maknanya belum tentu berkaitan dengan makna verba pangkal
sehingga harus dipelajari secara khusus.
Contoh:
(69) pemandangan 'panorama (yang dapat dipandang)'
pendapatan gaji; yang didapat'
pendengaran 'kemampuan mendengar/yang didengar'
pendirian 'pendapat yang dinyatakan/perbuatan mendirikan'
6) Penurunan Nomina dengan per-...-an
Konfiks per-...-an umumnya digunakan untuk menurunkan nomina
dari verba taktransitif yang berawalan her-., baik yang pangkalnya monomorfemis maupun yang polimorfemis. Seperti halnya dengan prefiks per-, konfiks per-...-an mempunyai tiga alomorf, yakni pel-...
-an, pe-... -an, dan per-... -an ^ang distribusinya paralel dengan distribusi pel-, pe-, dan per-. Alomorf pel-...-an hanya dapat ditambahkan
pada verba belajar untuk mendapatkan nomina pelajaran. Alomorf pe
...-an ditambahkan pada verba dengan be- dan per-...-an pada bentuk
pangkal yang lain.
Dari segi makna, konfiks per-...-an dapat menyatakan (a) hal
atau basil yang dinyatakan verba pangkal, (b) perbuatan yang dinyatakan
verba, (c) hal yang berkaitan dengan bentuk pangkal, dan (d) tempat yang
dinyatakan bentuk pangkal. Berikut disajikan contoh nomina turunan
dengan per-... -an berdasarkan maknanya.
a) Nomina dengan per-...-an yang diturunkan dari verba dengan berumumnya menyatakan hal yang dinyatakan bentuk pangkal.
Contoh:
(70) pergerakan 'hal bergerak
perjuangan 'hal berjuang'
perselisihan 'hal berselisih'
pertanian 'hal bertani'
peternakan 'hal beternak
b) Nomina dengan per-... -an yang diturunkan dari verba tertentu yang
berawalan ber- dapat bermakna 'perbuatan atau hasil perbuatan yang
dinyatakan bentuk pangkal'.
Contoh:
(71) percakapan 'perbuatan/hasil bercakap-cakap'
perkelahian 'perbuatan/hasil berkelahi'
perjanjian 'perbuatan/hasil berjanji'
pertemuan 'perbuatan/hasil bertemu'
perzinahan 'perbuatan berzinah'
c) Nomina dengan per-...-an yang diturunkan dari verba dengan
memper- umumnya bermakna 'perbuatan atau hasil perbuatan yang
disebutkan verba pangkal'.
Contoh:
(72) pergelaran 'perbuatan/hasil mempergelarkan'
perhatian 'perbuatan/hasil memperhatikan'
peringatan 'perbuatan/hasil memperingati/kan'
perkenalan 'perbuatan/hal memperkenalkan/berkenalan
pertunjukan 'perbuatan/hasil mempertunjukkan'
d) Nomina dengan per-... -an dapat pula diturunkan dari bentuk dasar
nomina dengan makna 'hal yang berkaitan dengan nomina pangkal'.
Contoh:
(73) perbengkelan 'hal yang berkaitan dengan bengkel'
perbukuan 'hal yang berkaitan dengan buku'
perhotelan 'hal yang berkaitan dengan hotel'
perkapalan '
Langganan:
Komentar
(
Atom
)